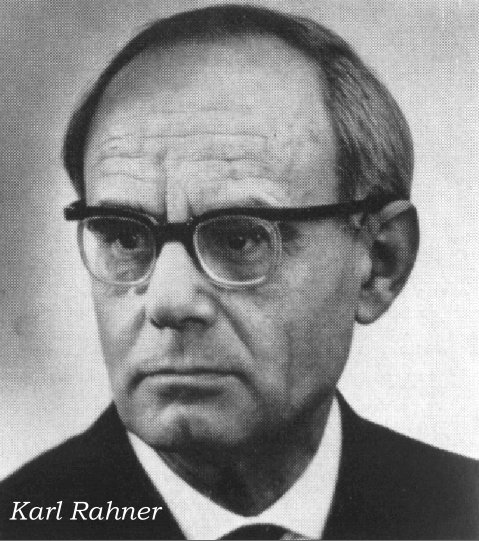terdiri dari berbagai bangsa. Bila diklasifikasi area tanah
, maka didapatlah dua bagian yang sangat penting. Bagian pertama adalah Tanah Tertutup dan yang kedua Tanah Terbuka.
saja yang mendiaminya. Tanah Tertutup ini seringkali disebut juga pedalaman
.
Sistem budaya di Tanah Terbuka sangat sesuai dengan karakternya saat itu. Di mana orang-orang
Batak
dengan tujuan ekonomi dan politik biasanya tidak ingin memonopoli
segala sesuatu di Tanah Terbuka. Bahkan cenderung orang-orang
Batak akan mengajak berbicara pedagang-pedagang asing dengan bahasa Melayu, sebuah bahasa yang menjadi Lingua Franca saat itu.
Orang-orang
Batak,
sangat pintar dalam memainkan peran mereka dalam persaingan komunitas
di bandar-bandar (pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal,
pasar-pasar dan pusat perekonomian. Tujuannya adalah agar komunitas
pedagang
Batak tidak terisolir dan teralienasi dari perkembangan perekonomian saat itu.
Oleh karena itulah Belanda seing kali menuliskan dalam laporan mereka bahwa bandar-bandar ekonomi tanah
Batak di pesisir dan kota-kota besar
Batak
lainnya sebagai berciri khas Melayu. Laporan VOC di abad ke-17
mengatakan bahwa Barus merupakan tanah pesisir yang berkarakter Melayu
dengan jumlah penduduk yang sebagian besar adalah orang
Batak.
Penduduknya, menurut Arendt Silvus, terdiri dari “Orang-orang Melayu
dari pesisir ini dan pesisir lain yang bercampur dengan orang-orang
Batak.” [Lihat Surat, Silvius to Pitt (1677), VOC 1322, f. 1328r.
Francois
Backer, seorang pegawai pertama perusahaan VOC, perusahaan Belanda yang
telah mendapat izin berdagang dari Sultan Barus (1672), dan orang
pertama yang melihat pelabuhan Barus, mengatakan bahwa menurut
penglihatan dan pemahaman umum yang didapatnya, penduduk Barus terlihat
sangat superior atau lebih tinggi kelasnya dari komunitas-komunitas
pesisir lainnya: “Mereka lebih mirip seperti Ketua-ketua ulama dari pada
pribumi yang brutal,” sambungnya. [Lihat, backer to Pits (1669), VOC
1272, f.1066v] Bahkan Silvius mengatakan bahwa penduduk Barus sebagai
orang yang penuh taktik, mempunyai kepentingan sendiri, tegar dan
diplomatis…” Silvius to Pits (1677), VOC 1322, f. 1328 r.
Penduduk
Barus pada tahun 1600-an merupakan penduduk yang terdiri dari berbagai
komuitas pedagang asing, Aceh, Minang, Tamil, Hindu, Kerinci, Siak dan
lain sebagainya selaian dari komunitas-komunitas pedagang. Sehingga
orang-orang
Batak dalam hal ini
pemerintahan Kesultanan barus, lebih memilih untuk menggunakan kebiasaan
dan bahasa yang sangat umum saat itu, yakni Melayu, agar dapat
mempertahankan para saugadar-saudagar kaya tersebut untuk menetap secara
permanen di Barus. Kehadiran mereka dapat terus memutar roda
perekonomian makro di Kesultanan Barus. Sebuah strategi dan taktik
ekonomi yang sangat jitu untuk mempertahankan Barus sebagai kota
pelabuhan tersibut dan paling banyak diminati asing saat itu.
Untuk
memastikan keamanan dan kenyamanan para saudagar-saudagar asing
tersebut, telah diangkat beberapa hulu balang untuk menempati berbagai
posisi, di antaranya Malim Muara dan Kepala Syahbandar untuk mencegah
intrusi dari bajak laut yang ingin mengacaukan perekonomian. Di antara
bajak-bajak laut yang paling menakutkan saat itu adalah mereka yag
berasal dari Belanda, Perancis dan Portugis. Beberapa kali para bajak
laut tersebut mengacaukan perekonomian di Barus agar supplai komoditas
dari Barus terhambat sehingga para saudagar Eropa lebih memonopoli
perdagangan. Sepertinya simbiosis saudagar picik dan kekuatan hitam
bajak laut tersebut berhasil membingungkan para saudagar-saudagar Cina,
Arab, India dan saudagar-saudagar Nusantara.
Melayu sebagai Tren Globalisasi Kultur RegionalBentuk dari pemerintahan
Batak
di Kesultanan Barus, yang pada saat itu dibuat dengan nuansa Melayu,
bersifat republik dan demokratik. Pusat urusan pemerintahan terdapat
disebuah istana dan tempat pertemuan publik yang disebut “balai”. Istana
ini sangat berbeda dengan istana kesultanan yang lebih kepada urusan
administrasi dan kediaman Sultan. Di Balai inilah segala urusan
kerakyatan dilakukan. Dilaporkan juga bahwa di sinilah setiap penduduk,
asing maupun lokal, melakukan protes dan komplen atau mengadukan
permasalahan mereka maupun untuk menyampaikan aspirasi politik kepada
Sultan yang diwakili oleh hulubalangnya di Balai. Para warga negara atau
gemeente, seperti yang dipahami Belanda, telah memainkan peran yang
aktif dalam urusan-urusan politik Kesultanan. [Lihat, Milner, Kerajaan,
hlm. 25]
Penduduk Kesultanan Barus yang terdiri dari kaum
bangsawan atau Orang Kaya dan kaum middle class, kelas menengah selalu
melibatkan diri dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Para pelaut
Belanda dengan cepat dapat mengenal sistem politik Kesultanan ini dan
berhasil menyogok para warga untuk mendapat rekomendasi dan tanda
persetujuan atas kehadiran mereka. Melalui rekomendari kelas menengah
inilah VOC, atau perusahaan Belanda dapat diizinkan oleh Sultan untuk
melakukan kegiatan ekspor impor di Kesultanan.
Melman mengatakan
bahwa adalah tekanan dari gemeente yang membuat pemerintah mengizinkan
Kompeni Belanda untuk beroperasi di Barus walaupun mendapat penolakan
maupun oposisi dari perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha Aceh.
(Backer to Pits (1669), VOC 1272, f.1066r.
Persaingan dagang
antara saudagar-saudagar Barus dengan saudagar-saudagar asing seperti
Aceh yang biasanya sangat lumrah dalam dunia perekonomian nampaknya
berhasil dirusak para pelaut Eropa. Sayangnya pemerintah melalui Sultan,
gagal mengatasi dan merumuskan undang-undang mengenai etika bisnis yang
legal dan larangan atas monopoli illegal sehingga pihak Eropa dapat
dengan leluasa mengobrak-abrik tatanan perekonomian kesultanan.
Menurut
laporan-laporannya, VOC bahkan menerapkan kebijakan rasial dengan
mendahulukan bertransaksi dengan para saudagar-saudagar Barus dari pada
para saudagar Aceh. Tujuannya adalah untuk mengisolasi pedagang Aceh.
Hal ini membuat kebanyakan pedagang pribumi Barus dan asing seperti Aceh
dan lain-lain protes dan menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan
kecurangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Belanda yang dapat merusak
iklim perdagangan yang sudah kondusif.
Namun, tampaknya, VOC
sudah mengenal sistem pemerintahan di Barus yang saat itu mempunyai
kelemahan yang sangat krusial. Pemerintahan Kesultanan Barus saat itu
dipegang oleh pemerintahan dualitas antara Dinasti Pardosi dengan
Pasaribu. Dahulunya, kedua dinasti ini memerintah di Kesultanan yang
berbeda namun dengan bertambahnya penduduk dan jumlah kota-kota
perekonomian, wilayah keduanya yang sama-sama di Barus dan sekitarnya
menjadi menyatu. Konsensus kedua dinasti telah banyak dicapai dalam
perjanjian-perjanjian antar penguasa dengan melakukan klasifikasi
kekuasaan dan demografi. Namun, dalam praktek, pemerintahan dualitas
tersebut sangat sulit direalisasikan dan rentan dengan konflik dan
korban adu domba.
Perusakan tatanan perekomian yang dilakukan
para pengusaha Belanda akhirnya berimbas kepada rusaknya tatanan
pemerintahan dan politik yang telah lama dibina oleh orang-orang
Batak. Dinasti Pardosi yang secara yuridis formal mempunyai gelar Raja Di Hulu dan Dinati Pasaribu dengan gelar Raja Di Hilir.
Pemberian
gelar tersebut sebenarnya sudah merupakan kompromi dan konsensus
bersama antara keduanya yang mencakup cakupan pengaruh, wewenang dan
geografi kekuasaan. Dimana Pardosi wilayah pengaruhnya ke Hulu Barus dan
Pasaribu ke Hilir Barus. Walaupun dipimpin oleh dua dinasti, Barus oleh
para saudagar-saudagar asing diakui sebagai sebuah kesatuan kesultanan
yang tidak terpisahkan. [Stapel dan Heeres, eds., Corpus Diplomaticum,
vol. 2, hlm 383-389]
Taktik pertama yang dilakukan oleh VOC
adalah dengan menimbulkan kecemburuan antar dua dinasti dengan
mengistimewakan Raja di Hulu dari Raja di Hilir walau keduanya sama-sama
mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Bersama Sultan saat
mengeluarkan surat izin beroperasi bagi VOC. Kadang-kadang juga, atas
dasar kepentingan ekonomi dan politik mengitimewakan yang Hilir daripada
yang di Hulu.
Walaupun pada awalnya taktik pecah belah ini tidak
terlalu dirasakan oleh kedua dinasti karena Raja Hulu dipanggil oleh
VOC dengan sebutan sebagai Raja dan yang Hilir sebagai perdana menteri.
Atau berbagai sebutan lain, yang kurang bermakna bagi pemerintahan Barus
seperti opper-Regent bagi Sultan Hulu dan mede opper-Regent untuk yang
di Hilir. [Backer to Pits (1669)]. Karena dalam pergulatan kedua dinasti
dalam sejarah memang sering terjadi saling merebut kekuasaan bahkan
dengan perang yang pada akhirnya terciptalah sebuah konvensi politik
bahwa Raja di Hulu merupakan Raja Tunggal dan di Hilir memegang posisi
Bendahara alias Perdana Menteri yang disetujui oleh kedua Dinasti.
Peta PolitikSecara
umum peta politik di Kesultanan Barus yang dihuni oleh rakyat yang
plural dan beragam, sangatlah komplek dan rumit. Kerumitan tersebut
semakin parah saat pemerintahan tetangga juga memback-up dan mendukung
jaminan keamanan bagi para komunitas dagangnya di ibukota Kesultanan.
Sultan
Aceh dikhabarkan beberapa kali menginterpensi kebijakan politik
Kesultanan agar dapat meningkatkan jaminan keamanan kepada
perusahaan-perusahaan Aceh dan para pengusahanya. Begitu juga dengan
Raja Minang yang melindungi kepentingan pengusahanya. Tidak dapat
dipungkiri begitu juga dengan Tamil, Arab, Siak Cina dan lain
sebagainya, seperti halnya Belanda dan VOC-nya.
Silvius
mengatakan bahwa pemerintahan Aceh telah melakukan langkah politik yang
sangat jitu dengan menggandengan Sultan Di Hulu dengan memberinya gelar
kehormatan [Silvius to Pits (1677). Sedangkan pemerintahan Minang lebih
suka untuk menggandengan Sultan Di Hilir yang merupakan orang
Batak
yang dilahirkan di Tarusan, Minangkabau. Dari laporan-laporan Belanda
dan manuskrip-manuskrip Kesultanan ditemuan bahwa pemerintahan Aceh
bahkan seringkali mengirim ekspedisi militernya untuk melindungi para
pengusaha Aceh di Barus. Diyakini kompetisi Belanda kontra para saudagar
Aceh telah sampai kepada persaingan bisnis yang sangat brutal yang
menghancurkan dan mengganggu seluruh sistem tatanan perekenomian
pemerintahan Kesultanan Barus.
Kedua bangsa, Aceh dan Belanda
telah saling tuduh menuduh dan saling mencurigai satu sama lain sebagai
bangsa brutal, pembunuh dan pembantai. Diyakini hal ini disebabkan antar
kedua bangsa ini telah terlibat dalam peperangan dan persaingan ekonomi
yang berujung kepada pembantaian antar keduanya. Propaganda saling
menyudutkan ini merupakan implikasi dari persaingan dagang yang sangat
brutal.
Friksi antar kedua Dinasti yang memerintah di Barus
dilaporkan semakin meningkat saat Sultan di Hulu mulai, mau atau tidak
mau, terlibat dalam persaingan tersebut. Sultan di Hulu mulai menarik
persetujuannya dengan menolak kehadiran Kompeni (VOC) yag mulai terlihat
sangat bermusuhan dan tidak bersahabat dengan para saudagar-saudagar di
Barus. Mereka memboikot transaksi dagang dengan VOC. [Kroeskamp, De
Weskust, Hlm 153 dan Backer to Pits (1669).
Sementara itu,
Kompeni atau VOC berhasil menyelamatkan muka dengan berlindung atas nama
Sultan di Hilir yang lebih memilih untuk bersikap fleksibel dengan
Kompeni yang dimusuhi oleh saingannya yang Di Hulu. Orang-orang Belanda
mengkalim bahwa kehadiran mereka didukung oleh Sultan Hilir untuk
menciptakan keseimbangan kekuatan dengan hadirnya pasukan Aceh Di Hulu.
[ibid., f. 1067v]
Jalur-jalur Ekonomi; Antara Pesisir dan PerbukitanKonstelasi politik
Batak,
khsusunya antara kedua Dinasti yang memerintah tidak saja seputar peran
asing tapi juga mencakup jalur-jalur perekonomian. Saudagar-saudagar
Batak
yang berperan sebagai pengumpul komoditas-komoditas dari pegunungan
sekitar Barus, seperti Pakkat, Dolok Sanghul, Dairi dan lain-lain, juga
terlibat dengan para Saudagar
Batak
lainnya yang menjadi pengumpul di wilayah-wilayah antara Barus dan Air
Bangis. Dari areal ini, kamper dan benzoin di dapat di Sibuluan, Batang
Toru, Batu Mundam, Tabujang, Natal dan Batahan. [Melman to Pits (1669).
Sultan
Hulu lebih mempunyai legitimasi kepada para saudagar kelompok pertama
yang Sultan Hilir lebih dilegitimasi oleh kelopom kedua. Kelopok
pertama, yakni mereka yang berasal dari pegunungan sekitar Barus terdiri
dari mereka yang berasal dari Dairi, Marga Mukkur, Meha, Simbolon,
Marbun, Simanullang, Simamora, Pardosi, Sigalingging, Pohan, Naipospos
dan lain sebagainya. Sementara yang kedua lebih banyak dari Mandailing,
Pasaribu, Hutagalung dan lain sebagainya.
Menurut Melman, peperangan antara dua kelompok saudagar
Batak
seringkali terjadi. Namun kedua kelompok tersebut akan sangat menahan
diri untuk memerangi pemerintahan Barus. Satu kelompok akan mencegah
kelompok lainnya untuk memerangi Barus. Walau seandainya pada saudagar
Batak itu ingin melakukannya, seperti kudeta, dapat saja mereka lakukan, namun para pelaku pasar dan ekonomi
Batak sangat sadar atas perlunya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Posisi
inilah yang kemudian dipahami oleh para saudagar asing. Banyak
pengusaha Aceh, Melayu dan Arab yang melakukan kontak dagang langsung ke
pegunungan-pegunungan yang biasanya didominasi dan dimonopoli oleh para
saudagar
Batak. Kehadiran mereka di sana dihormati oleh para pelaku ekonomi
Batak asal saja patuh dengan etika-etika ekonomi yang ditentukan oleh adat.
Tampaknya Kompeni Belanda juga ingin ikut-ikutan. Namun kehadiran perusahaan VOC di pedalaman
Batak dengan tegas ditolak oleh para saudagar
Batak
dan raja-raja huta karena melihat perangai dan perilaku orang Kompeni
yang sudah dikenal brutal dan kasar apatah lagi sangat rasialis dengan
menganggap ras mereka lebih tinggi dari pribumi yang diejeknya sebagai
primitif, budak dan pemakan orang.
Hubungan dagang antara pedalaman
Batak dengan VOC sama sekali tidak ada kecuali dengan perantara para saudagar di Barus yang lebih dipercaya oleh orang-orang
Batak. [Mengenai lebih percayanya orang
Batak
dengan Sultan di Barus dari pada Kompeni lihat Melman to Pits (1669)].
Hal itulah yang ditemukan Melman di Barus dan dia melaporkan kondisi
tersebut kepada atasannya di kantor pusat VOC di Padang tentang
keengganan orang
Batak pedalaman melakukan hubungan dagang dengan Kompeni.
Namun, Kompeni dengan strategi jitunya tetap saja mendapat komoditas yang mereka inginkan dengan membeli komoditas-komoditas
Batak
melalui Sultan Hilir yang lebih bersikap lunak kepada Kompeni.
Sementara itu dari pihak Sultan Hulu sama sekali masih memboikot
perdagangan dengan Belanda.
Walau bagaimanapun, boikot dan
embargo ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Di Hulu terhadap Kompeni atas
kebrutalan dan kecurangannya telah berhasil mengurangi keuntungan
perusahaan yang selama ini selalu didapat secara berlipat ganda.
Pada
tahun 1671, perubahan konstelasi politik regional mulai bergeser.
Kekuatan Aceh mulai menarik pasukannya dari Barus seiring dengan mulai
membaiknya peta politik saat itu. Belanda mulai mengambil langkah untuk
memperbaiki perangai mereka dengan pihak penguasa. Backer seorang
pegawai Kompeni, setelah dengan susah payah berhasil mendapat simpati
dari Sultan Di Hulu untuk menjamin supplai produk-produk dari pedalaman
Batak. Sultan, menerima iktikad baik tersebut dan bahkan menjamin akan meningkatkan pengaruhnya di pedalaman
Batak untuk segera mengirim komoditas yang diinginkan oleh Kompeni. [Backer to Pits (1671)].
Tahun
1694, Kompeni mengurungkan niatnya sementara untuk menerapkan kebijakan
adu domba dan pecah belah terhadap Barus. Mereka mengakui kedaulatan
dan otoritas Kesultanan Barus yang dipimpin oleh kedua Dinasti tanpa
membeda-bedakan satu sama lain. Konvensi Kesultanan Barus yang
menganggap Sultan Di Hulu sebagai penguasa dan Sultan di Hilir sebagai
perdana menteri mulai diakui secara permanen. Pihak pengusaha Belanda,
untuk sementara, tidak lagi berusaha mengadu domba dengan
mengistimewakan pihak Hilir.
Barus, Dairi dan Batak Dipecah BelahDalam
dokumentasi Belanda pada tahun 1694, mereka mulai sadar bahwa mereka
tidak akan bisa bertahan di Barus, di tengah arus kompetisi ekonomi yang
mulai ketat, tanpa dukungan dan kemurahan hati Sultan di Hulu. Hal itu
dipahami oleh Belanda, karena dalam sebuah langkah brutal untuk
melenyapkan Sultan di Hulu oleh Belanda, telah mengalami kegagalan
karena dukungan sebuah pasukan ekspedisi militer yang terdiri dari
kepala-kepala huta orang-orang Dairi yang setia kepada Sultan Hulu pada
tahun 1693, setahun sebelum pengakuan Kompeni tersebut.
Setelah
supremasi dan otoritas Sultan Di Hulu kembali ke semula, Sultan
Minuassa, Sultan di Hulu yang memerintah saat itu, dilaporkan bermusafir
ke Dairi untuk pengasingan sementara di pegunungan di belakang Singkil.
Dukungan
yang diberikan oleh para raja-raja huta Dairi terhadap Sultan Di Hulu
mengejutkan orang-orang Belanda, padahal sebelumnya telah ada perjanjian
antara Kompeni dengan orang-orang yang dilakimnya sebagai tetua Dairi
untuk memindahkan loyalitas mereka dari Sultan Hulu ke Hilir.
Dalam pengasingan Sultan, pihak Belanda yang tidak pernah putus asa untuk merusak tatanan hidup orang
Batak
di Kesultanan Barus mulai mendekrasikan Sultan di Hilir menjadi Raja
Barus. Untuk mendukung kebijakan mereka, orang-orang Dairi mulai
didekati untuk menghianati kembali Sultan mereka. Hal ini tampaknya
mendapat keberhasilan.
Pada tahun 1698, Sultan Minuassa yang
mengasingkan diri sementara di Dairi kembali ke Barus, namun dia
mendapati kekuasaanya telah hilang dan lenyap. Belanda bersikukuh bahwa
dia bagi mereka hanyalah bara-antara bagi orang Dairi. Belanda berhasil
mengangkat Sultan Hilir sebagai pemerintah boneka yang dapat disetir
oleh perusahaan VOC.
Sultan Minuassa tidak menerima kecurangan
yang dialaminya. Pada tahun 1706, dia berhasil menggalang kekuatan,
khususnya dari semarganya di Dairi dan Singkel, untuk mengembalikan
kehormatan dan harga diri sebagai Sultan penguasa Barus. Orang-orang
Batak
di pegunungan sekitar Barus juga mendukungnya. Usaha ini berhasil
mengembalikan tahta dan istananya. Pada tahun 1709, paman Sultan
Minuassa yang bernama Megat Sukka atau Sultan Bongsu Pardosi berhail
melakukan gempuran mematikan terhadap lawan-lawannya, atas nama
kedaulatan dan tahta Sultan Hulu, dan berhasil menguasai seluruh Barus.
Usaha ini mencapai kemenangan yang fantastis sejak sebelumnya pihak
Sultan di Hulu berhasil melobbi pihak Kerajaan Aceh untuk mengirimkan
pasukan pendukung.
Namun pihak Sultan di Hulu tidak ingin
memerintah secara egois di Barus. Kedaulatan Sultan di Hilir juga
dikembalikan. Sekali lagi kombinasi Hulu dan Hilir dalam memerintah
Barus seperti dahulu kala berhasil dikembalikan. Sultan Hilir dalam
suratnya kepada Kompeni di Padang mengatakan bahwa Barus telah kembali
ke sistem pemerintahan semula, yakni pemerintahan yang dikuasasi oleh
dua dinasti. [Lihat surat Raja Barus (hilir) kepada VOC (1709), VOC
1777].
Orang-orang Batak BersatuPada 1736-1740 merupakan tahun yang sangat krusil bagi bangsa
Batak.
Pada saat ini orang-orang Dairi membulatkan tekadnya untuk mendukung
tahta dan kedaulatan Sultan Di Hulu yang mencakup semua wilayah Dairi,
Sionom Hudon, Pakpak dan Simsim.
Demikian pula halnya dengan raja-raja
Batak dari pedalaman. Para raja-raja
Batak ini berkenan pula mengirimkan pasukannya ke Barus untuk menghalau teror yang dilakukan oleh kompeni dan Belanda.
Penduduk
Sorkam dan Korlang, berhasil dimobilisasi oleh Raja Simorang dari
Silindung untuk bersatu dan bersama-sama mengusir Kompeni atau VOC.
Beberapa kali perang terjadi antara kedua belah pihak.
Sementara
itu, Dinasti Sisingamangaraja VIII, yang bernama Ompu Sotaronggal dan
bergelar Raja Bukit memimpin pasukannya dari tanah
Batak
untuk mendukung pasukan Barus bersama pasukan Kerajaan Aceh untuk
memberi perlindungan kepada Sorkam dari pembunuhan oleh Kompeni. Begitu
heroiknya Raja Bukit dalam pertempuran tersebut, sehingga orang-orang
Eropa yakin bahwa Raja Bukit adalah orang Aceh.
Aliansi beberapa
pasukan yang dipimpin oleh Raja Bukit ini berhasil menggetarkan pihak
Belanda sehingga namanya dikenal sampai ke Inggris. [Anne Lindsey, “The
Private Trade Of The British In West Sumatera” 1735-1770” [Ph.D
Disssertation, University of Hull, 1977], p. 122.
Ompu Sotaronggal merupakan Sisingamangaraja VIII, keturunan Dinasti Sisingamangaraja yang memerintah di pedalamanan
Batak.
Silsilah dinasti Sisingamangaraja sampai abad ke 18 adalah pertama Raja
Sisingamangaraja I dengan nama asli Raja Mahkota atau Raja Manghuntal
memerintah tahun 1540 s.d. 1550. Yang kedua SM Raja II, Raja Manjolong
gelar Datu Tinaruan atau Ompu Raja Tinaruan memerintah 1550 s.d 1595.
Yang ketiga, SM Raja III, Raja Itubungna, 1595-1627. Yang keempat SM
Raja IV, Tuan Sorimangaraja 1627-1667. Yang kelima, SM Raja V, Raja
Pallongos, 1667-1730. Yang keenam SM Raja VI, Raja Pangolbuk, 1730-1751.
Yang ketujuh SM Raja VII, Ompu Tuan Lumbut, 1751-1771 dan yang
kedelapan SM Raja VIII, Ompu Sotaronggal, gelar Raja Bukit 1771-1788.
Diyakini bala bantuan dari Bakkara tersebut direalisir karena kedua kerajaan, Kerajaan
Batak
dan Kesultanan Barus merupakan dua negara yang merdeka yang saling
mengakui kedaulatan satu sama lain. Kerjasama keduanya sudah terjadi
sejak dahulu kala, khususnya dalam hubungan ekonomi dan adat budaya.
Keduanya semakin menyatu setelah keduanya merupakan sekutu dekat
Kerajaan Aceh untuk mengatasi berbagai masalah.
VOC Bangkrut, Kompeni HengkangBangkitnya
Kesultanan Barus dari tekanan amoral Kompeni, ternyata mengembalikan
keamanan dan kenyamanan dalam kesultanan yang membuat bangkitnya
saudagar-saudagar yang bukan Belanda dalam perekonomian.
Perusahaan-perusahaan
Aceh yang berkompetisi langsung dengan VOC mulai bangkit dari isolasi
yang dibuat oleh Kompeni tersebut. Penduduk pribumi mulai sadar dengan
perangai dan perilaku Belanda yang makin lama makin meniadakan
eksistensi mereka sebagai pribumi. Orang-orang
Batak
mulai menghindarkan diri untuk berhubungan dan bertansaksi secara
ekonomi dengan pihak Belanda. Arogansi dan kepicikan Belanda yang
menggap pribumi sebagai primitif, kampungan dan pemakan orang semakin
membuat penduduk pribumi yakin dengan ke’aneh’an perdaban Kompeni.
Orang-orang
Batak
tetap melakukan bisnis dengan semua bangsa-bangsa termasuk Arab, Cina,
India, Aceh, Siak, Bugis dan Inggris serta Perancis yang datang
belakangan. Pada tahun 1778 kompeni Belanda atau VOC di Barus bangkrut
dan mereka menarik diri dari Kesultanan Barus.
Masuknya InggrisKesultanan
Barus berhasil membangun kembali peradaban mereka. Beberapa lembaga
pemerintahan dan sosial berhasil dibangun kembali sejak keamanan dan
ketertiban berhasil dipertahankan. Sejak akhir abad ke-18 itu,
masyarakat pedagang di Kesultanan Barus mulai melihat prospek kecerahan
perekonomian setidaknya suasana persaingan ekonomi mulai fair, adil dan
beretika.
Pada tahun 1814, John Canning, seorang penyusup dan
pegawai perusahaan Inggris berhasil memasuki Barus setelah sebelumnya
perusahaan Inggris telah membuka kantor cabangnya di kota pelabuhan
Natal. Canning diberi misi untuk memata-matai dan mengukur kekuatan
pengusaha Aceh dan pengaruh Kesultanan Aceh di Barus. Menurut informasi
orang-orang Eropa saat itu, pasukan Aceh telah ditempatkan secara
temporer di Taruman, sebuah wilayah Barus perbatasan antara Kesultanan
Barus dan Aceh. Wilayah Taruman itu mencakup Singkil sampai Meulaboh.
Paska bercokolnya kembali Belanda, wilayah Taruman berhasil
memproklamirkan diri menjadi Kesultanan Tarumon dengan sultan yang
berasal dari
Batak Singkil serta dengan pengakuan dari Aceh.
Pada
tahun ini (1814) penguasa Barus yang tunggal dari Hulu bernama Sultan
Baginda Raja dengan perdana menteri dari Hilir. Menurut Canning,
perusahaan dan pengusaha-pengusaha Aceh berdomisili di Tapus. Sementara
itu Taruman bagian utara Barus telah diangkat seorang Aceh untuk menjadi
gubernur oleh Sultan Baginda yang bernama “Lebbe Dappah”. Menurut
Canning pula bahwa Kesultanan Barus merupakan negara yang sangat penting
untuk menahan pengaruh Aceh ke Selatan, khususnya Natal.[lihat Captain
J. Canning, 24 November 1814, Sumatra Factory Record., vol.27]
Laporan-laporan
mata-mata ini berhasil melihat secara jelas peta perpolitikan di Barus
paska hengkangnya Belanda. Menurutnya, Sultan di Hilir, sebenarnya sudah
tidak berdaulat lagi, sejak mereka hanya bagian dari pemerintahan
Sultan Barus (Di Hulu) berbeda dengn laporan-laporan Belanda yang saat
itu masih terus saja berhipotesa mengenai kondisi kontemporer
Kesultanan.
Sementara itu, konstelasi politik dunia mulai
mengalami kemajuan Beberapa perusahaan-perusahaan Eropa mulai mendapat
keuntungan yang berlipat ganda setelah mengeruk kekayaan dan
mengekplotasi berbagai negara dan wilayah terbelakang di Asia dan Afrika
dan juga Amerika Latin.
Belanda Kembali, Kali ini Untuk MenjajahPada
tahun 1820, Belanda kembali lagi ke Barus kali ini maksud mereka bukan
untuk berdagang tapi menjajah sepenuhnya Barus. Selang lima tahun
Belanda berhasil menguasai para pejabat pemerintahan dengan maksud untuk
memperkuat jaringanya.
Kali ini Belanda masuk dengan pasukan
yang sangat dan canggih saat itu. Kehadiran mereka di dipegunungan juga
mendapat tantangan oleh orang-orang
Batak Padri yang tidak setuju dengan konsep hisap darah dan penjajahan ala Belanda tersebut.
Pada
tahun 1825, perpecahan antara kedua penguasa di Barus berhasil
diciptakan, Ridder de Steurs mengklaim bahwa salah satu Sultan telah
meminta Bantuan dari Belanda di Padang untuk mengirim pasukan membela
salah satu Sultan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Belanda untuk
mengirim pasukan lebih banyak tanpa mendapat perlawanan dan protes dari
raja-raja
Batak di berbagai
tempat. Walaupun Belanda telah datang dengan pasukan bersenjata lengkap
tetap saja mereka harus mengambil langkah yang jitu agar langkah
tersebut tidak mengalami kegagalan yang fatal.
Usaha untuk
menjajah dan mencaplok secara total Barus terus dilakukan namun selalu
mendapat perlawanan dari Rakyat. Pergulatan, peperangan dan pertikaian
terus terjadi sampai tahun 1839. Pada tahun ini Belanda berhasil
menguasasi Barus setelah sebelumnya Belanda berhasil menguasai Bonjol
pada tahun 1837. Setelah menguasasi Bonjol, pusat pasukan Padri Minang
dan setelah banyaknya orang-orang Padri
Batak
tewas dan gugur mempertahankan Air Bangis, pasukan Belanda dapat
mengumpul kekuatan penuh untuk menguasasi Barus dua tahun kemudian yakni
1839-40. Walaupun begitu, Kesultanan Barus masih tetap eksis di bawah
penjajahan dengan gelar Tuanku dan bukan Sultan.
Seorang penyusup
Belanda yang bekerja untuk kepentingan militer, H.N. van der Tuuk yang
pada tahun 1851, berhasil menyusup sampai ke pedalaman Batak. Walaupun
Barus dikuasasi, namun pedalaman
Batak tetap merdeka sampai tahun 1907.
Para penyusup tersebut diinfiltrasikan oleh Belanda dengan tujuan mengkeroposkan sistem sosial dan adat orang-orang
Batak. Penguasaan terhadap tanah
Batak adalah sangat penting untuk menyempurnakan kekuasaan Belanda di Sumatera yang hanya tinggal Aceh dan
Batak tersebut.
H.N. van der Tuuk, dengan bantuan para ketua-ketua kampung di Barus yang terdiri dari pada
Batak muslim yang menjadi pemandu, berhasil memasuki tanah
Batak.
Dari sana dia berhasil memetakan dan menarik kesimpulan yang mesti
diperhatikan oleh para penyusup Belanda berikutnya. Di antaranya adalah
keharusan memelihara babi dan mengisolasi masyarakat
Batak
Muslim dan kelompok “pitu hali malim pitu hali solam” dari yang
pelebegu. [Lihat Lihat: R. Nieuwenhuys, H.N. van Der Tuuk: De, Pen in
Gal Gedoopt, (Amsterdam, 1962) hal: 81-84] Dengan begitu orang
Batak akan mudah ditaklukkan.
Pada
tahun 1851, Sultan Di Hulu, dari Dinasti Pardosi mulai secara
pelan-pelan dikurangi otoritasnya. Dia mulai dilarang untuk menggunakan
stempel kerajaan dalam membuat surat. Ini berarti kekuasaannya sudah
tumpul dan puntung karena sudah tidak boleh mengeluarkan perintah dan
keputusan. Kondisi ini membuat Tuanku di Hilir merasa bahagia menjadi
penguasa tunggal yang tersisa dengan dukungan Belanda. Namun belum
lengkap kebahagiaan yang dirasakan olehnya, Belanda menetapkan keputusan
sama pada tahun 1852 terhadap Tuanku di Hilir.
Untuk semakin
mengerdilkan Barus yang pernah membangkrutkan Belanda, pihak penjajah
kemudian menunjuk Sibolga yang dipimpin oleh keturunan Tuanku Dorong
Hutagalung sebagai pusat perekonomian menggantikan Barus. Para saudagar
mulai dipersulit beraktivitas di Barus. Beberapa kali, dalam menumpas
kekuatan kemerdekaan dari pribumi, Belanda mengambil jalan pintas dengan
membakar dan menghancurkan semua desa-desa dan penduduk Barus.
Lama-kelamaan bahkan sampai sekarang Barus tinggal hanya puing-puing. Di
atasnya, penduduk Barus yang sudah sangat terpuruk secara ekonomi dan
mental mulai membangun tempat tinggal mereka kembali dari pelepah daun
dan rumbia, akibatnya Barus dan orang-orang
Batak kembali ke zaman kegelapan, saat orang-orang
Batak masih hidup telanjang berkelompok dan nomaden.
Para
keturunan Sultan dan Tuanku Barus hanya boleh dikenal oleh penduduk
dengan sebutan kepala kampung atau desa atau kepala kuria. Sedapat
mungkin Belanda membatasi gerak dan usaha mereka untuk berbicara.